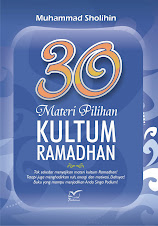Oleh: Nurus Shalihin Djamra
(Direktur Litbang Nagari Institute)
Kekerasan dan agresivitas bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari suatu sindrom. Ia merupakan bagian dari sebuah sistem yang memungkinkannya terjadi, baik oleh dominasi berlebihan, birokrasi kaku, kelas-kelas sosial.
(Erich fromm: 1973)
Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada selasa (03/12/08) Sumatera Barat terhenyak oleh berita perkelahian atau tawuran antara dua kubu mahasiswa di kampus IAIN “IB”-Padang, yang kata banyak orang adalah kampus Islami tapi kenyataannya amat berseberangan. Digambarkan; Suasana pukul 18.30 saat itu sempat mencekam, karena satu kelompok mahasiswa yang berada di luar kampus melakukan koordinasi sambil menunggu rekan-rekan lainnya, seolah akan terjadi perang hebat. Benar saja, tawuran tidak dapat dihindari sebagai akibat pemukulan, dan pelecehan yang sebelum telah terjadi terhadap salah satu kubu. Jauh sebelum kekerasan di IAIN, kekerasan, baik dalam bentuk tawuran, perkelahian telah mengeruyak di kampus-kampus di Indonesia, kekerasan di kampus ini telah mengoyak institusi perguruan tinggi sebagai fabricated bagi kaum intelektual dan moralis.
Kekerasan yang mengeruyak di kampus-kampus di nusantara dilatari oleh berbagai faktor, minsalnya di IAIN “IB”-Padang, dan di UNP (Universitas Negeri Padang) tawuran dan perkelahian antar mahasiswa disebabkan oleh pelecehan terhadap satu kelompok, kemudian ditimpali dengan tindakan kekerasan oleh kubu yang dilecehkan. Namun lain lagi dengan kekerasan dan kerusuhan yang terjadi pada kampus ISI Denpasar (18/9/08), sebagaimana yang dilansir oleh Detik.com bahwa kisruh yang berbuntut kekerasan ini dipicu oleh politisasi pada saat Pilrek. Dalam bentuk lain, Bentrok antar mahasiswa kembali terjadi di Universitas Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 17 November lalu. Terik matahari seolah menjadi saksi atas insiden yang melibatkan mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa Politeknik Negeri Kupang. Ketegangan dua kelompok mahasiswa itu dipicu saling ejek yang bermuara pada salah paham. Emosi akhirnya memuncak dan berujung pada tawuran. Ketika itu mahasiswa teknik dipukul mundur. Situasi semakin panas saat mahasiswa teknik balik menyerang. Perang batu pun tak terhindarkan. Sementara aksi saling serang terjadi silih berganti (liputan6.com: 30/11/08). Beberapa kasus ini setidaknya cukup untuk menjadi fakta betapa kini kampus telah berubah menjadi persemaian kekerasan jenis baru. Kenapa?
Memahami trend kekerasan di kampus, agaknya tidak semudah memahami kekerasan dalam rahah publik lainnya. Ini terletak pada kompleksitas yang menyebabkan kekerasan di kampus. Apalagi kekerasan di kampus bukan hal biasa dan tidak lumrah. Hal ini disebabkan citra yang terlanjur dilekatkan pada kampus sebagai ruang sosial yang semestinya menjadi subjek moral melalui agen-agen moralis yang diproduksi di kampus. Namun kini, seiring merebaknya kekerasan di kampus, dunia perguruan tinggi kian tersudut, tergelepar tak berdaya dalam “sanksian” masyarakat—seolah pergurun tinggi tengah dirudung “kegagalan” hebat.
Medan Baru Kekerasan
Kekerasan di kampus telah menjadi ekstasi jenis baru bagi pelaku kekerasan. Karenanya, kekerasan itu berulang, bermutasi, dan menjangkiti kampus lainnya. Dalam konteks ini, tidak berlebihan jika Erich Fromm memaknai kekerasan sebagai sebuah sindrom dan seketika menyebar dan menghancurkan sendi-sendi sosial. Kekerasan sesungguhnya tidak tunggal, Ia merupakan bagian dari sebuah sistem yang memungkinkannya terjadi, baik oleh dominasi berlebihan, birokrasi kaku, kelas-kelas sosial. Ini lebih dekat disebut sebagai faktor sosial-kultural yang menyebabkan kekerasan.
Dalam bentuk yang lain, kekerasan juga disebabkan oleh faktor subjektif, yang diistilahkan oleh Erich Fromm dengan “trance”. Trance ini merupakan kondisi mental dan spritual yang mencapai keadaan puncak tatkala jiwa secara tiba-tiba naik menuju tingkat pengalaman yang jauh melampaui kenyataan sehari-hari, sehingga mencapai puncak kemampuan diri dan kebahagian yang luar biasa, diiringi oleh trance dan kemudian pencerahan kala inilah seorang individu mengalami ekstasi personal dan bahkan komunal. Dalam ekstasi ini orang tidak lagi mengenal dirinya. Ia sama sekali menjadi yang lain. Ada kekuatan lain yang mengendalikannya. Ia tidak lagi menjadi dirinya ketika menikmati ‘ekstasi’, termasuk ekstasi penghancuran.
Kekerasan adalah hal yang amat kompleks. Hal ini setidaknya disebabkan oleh kompleksitas faktor yang menyebabkan tindakan kekerasan. Karena itu, untuk memahami kekerasan “kita” mesti mengindentifikasi kompleksitas gesture sosial yang ada disekitar kekerasan berlansung. Berkenaan dengan ini, John Gunn di dalam Violence In Human Society mengutarakan bahwa bencana krisis kemanusian di dalam sebuah masyarakat terjadi bila ikatan positif atau perekat telah hancur hingga berbutut pada kekerasan dan membentuk piramida korban. Dalam locus inilah, kekerasan di kampus menarik untuk dianalisis.
Jika ditarik ke belakang, kekerasan di Indonesia telah membawa bangsa ini kedalam batas-batas irrasionalitas tindakan, entah itu sebagai reaksi dari dominasi ataupun kelas sosial—seolah “kita” sedang diserang oleh gejala sentimental akut yang amat destruktif melalui kekerasan. Ini telah melampaui apa yang selama ini disebut sebagai wilayah kebangsaan, moralitas, cinta, dan persahabatan.
Kita semakin gagap ketika kekerasan dalam tubuh bangsa ini menjalar liar, hingga menjamahi wilayah yang sarat dengan moralitas yaitu dunia pendidikan. Kengerian bercampur aduk dengan kemirisan tatkala menatap dunia pendidikan “kita” hari ini. Jika dalam rimba politik kekerasan menjadi hal rasional, tapi tentu tidak rasional dalam dunia pendidikan. Namun kini, dengan parade kekerasan, entah berbentuk penyiksaan, pelecehan, perkelahian massal—membuat dunia pendidikan, terutama kampus berada dalam wilayah abu-abu; sebagai sphere untuk kaum moralis sekaligus menjadi ranah, ruang baru berjangkitnya tindakan kekerasan jenis baru.
Akankah sama dunia pendidikan “kita” saat ini dengan dunia politik? Di mana, di kampus telah kian kacau, karena di dunia ini kian berseliweran nilai-nilai, kekuatan yang mampu membuat aktor pendidikan lupa diri, lupa identitas dan lupa merawat eksistensialis-Nya. Dunia politik saat ini tak disangah oleh banyak orang sebagai dunia “kacau”, dunia penuh intrik, dunia dimana menjadi ruang bagi kebencian, kesumat—semuanya diarahkan pada satu puncak, yaitu kekuasaan. Tapi mungkinkah dengan parade kekerasan, dunia kampus sebagai “ikon” pendidikan juga mengalami kekacauan yang sama hebatnya dengan dunia politik “kita” saat ini. Dalam bahasa eksistensialis, betapa masyarakat kampus tidak lagi mampu merawat hidup dan eksistensi. Mereka membiarkan hidup dalam kondisi ketidakterawatan. Semua energi ditujukan hanya untuk merawat puncak-puncak kebahagian semata, hingga ikatan-ikatan digantikan dengan dominasi, saling tumpang tindih. Para dosen saling berebut mangsa melalui eksploitasi terhadap para mahasiswa dan mahasiswa pun diposisikan sebagai mesin, tak lebih. Dalam ujung yang lain, mahasiswa pun sibuk membangun citra diri yang sepenuhnya amat narsistik. Demikiankah?
Kekerasan di kampus makin menguratkan betapa perkembangan masyarakat Indonesia, setidaknya berapa dekade belakangan ini—dibanyangi oleh perubahan sosial yang cukup hebat. Di mana pergerakan masyarakat dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain. Dari kondisi “ekstasi” politik yang hanyut dalam heroik pencitraan, persaingan darwinian bergerak dan bermutasi dalam “ekstasi kekerasan” ke dalam dunia pendidikan. Benang merah yang dapat di utarakan dari kondisi ini, dunia pendidikan sedang dalam sengkarut kekakuan, egosentrisme kekuasaan. Hingga tak ada lagi ikatan-ikatan yang dapat mempertahankan emosional dalam dunia kampus. Alhasil, dunia pendidikan sedang berada pada tahap kehancuran karena didorong oleh transisi values sistemik yang mengendap dalam diri dan setiap aktor dalam kampus.